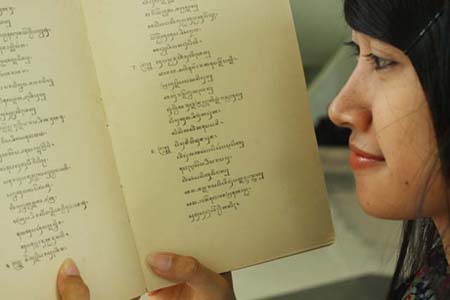Cerpen Budi Palopo
MATAHARI mengirim bayangan hitam kepada seluruh benda yang tak tembus pandang. Saya baru saja membuka jendela ketika peristiwa itu terjadi. Bayangan hitam selalu mengikuti setiap gerak seorang bocah perempuan yang tengah asyik menggores-gores tanah dengan sebilah tatal kayu di sekitar tubuh boneka berlumur darah yang tergeletak di pelataran rumah. Ia seakan membuat tengara kesedihan bergaris-garis tanpa aturan di tanah pijakan, untuk mengenang boneka yang dianggapnya telah mati terbunuh.
Saat itu juga, secara kebetulan, dari rumah seorang tetangga yang sedang berhajat mengkhitan anaknya, saya mendengar irama tembang langgam Jawa yang tersuarakan lewat tape recorder dengan lirik yang cukup menyentuh: “…golekan, kae golekane sapa. Yen sira tansah dadi golek-golekan, ingsun mengko entek mimis pira”.
Matahari secara perlahan mengurang panjang bayangan hitam yang telah terkirim ke seluruh benda yang tak tembus pandang. Seorang bocah perempuan bertelanjang kaki itu masih juga berusaha mendekatkan diri pada boneka yang telah dibuang oleh bapaknya sendiri. Sementara, bayangan hitam terus mengikuti segala gerak yang dilakukannya.
Saya kurang tahu persis bagaimana awal-mulanya, sehingga peristiwa itu bisa terjadi. Kalau toh boleh menduga, mungkin saja Rah –begitu panggilan bocah perempuan itu—oleh bapaknya dianggap telah berani membantah perintah.
Boleh jadi, Rah terlalu asyik bermain anak-anakan. Boneka plastik yang dimilikinya, pagi-pagi sekali telah dikudang-kudang dan diemban-ayunkan. Pagi-pagi sekali ia telah mengajari boneka untuk bisa berbicara dengan bahasa manusia. Tak menutup kemungkinan, Rah saat itu juga meniru-niru gaya Ria Enes ketika berdialog dengan boneka Suzannya. Rah pun mempertanyakan soal cita-cita boneka mainannya. Dan, karena boneka tak bisa bicara, Rah terpaksa menjawab sendiri pertanyaan yang telah dilontarkannya: “Cita-citaku, ingin jadi presiden…!”
Mungkin karena terlalu asyik bermain anak-anakan, terlalu sibuk berusaha mengajari boneka untuk bisa berbicara dengan bahasa manusia, akibatnya Rah tak bisa lagi mendengar suara panggilan bapaknya. Akhirnya, Rah kena marah. Boneka yang tengah dipeluknya mendadak direbut dan dibuang oleh bapaknya sendiri. Setidaknya, begitulah dugaan saya. Dan, tentu saja, sampeyan pun bisa mengumpulkan sejumlah dugaan yang lainnya.
Yang jelas, saya baru saja membuka pintu jendela ketika peristiwa itu terjadi. Saya melihat ada sebuah boneka plastik berlumur darah tergeletak di pelataran rumah, Saat itulah, dengan langkah tertatih, Rah datang mendekat dan menangisinya.
Tak lama kemudian, seorang lelaki yang jari-jari kedua tangannya masih belepotan darah sapi, datang menghardik. Rah dipaksa untuk segera meninggalkan boneka. Tapi, Rah menanggapinya dengan gelengan kepala. Rah menolak. Rah memilih diam di tempat untuk terus menggores-gores tanah di sekitar boneka dengan sebilah tatal kayu yang dipegangnya. Akibatnya, tangis Rah kian menyayat. Sebab, lelaki yang berprofesi sebagai tukang jagal sapi itu mencengkeram lengan kirinya. Rah diseret, dan terus diseret-seret. Kendati meronta, Rah tetap dijauhkan dari boneka-mainannya. Alasannya sederhana: Rah harus mandi sembari menghafal teks pancasila sebelum pamit berangkat sekolah dengan mencium tangan bapaknya.
[]
ENTAH sudah berapa kali saya mendengar Rah menangis. Yang jelas, setahu saya, Rah sering menangis. Bahkan, suatu hari, di awal Agustus, setelah melihat ada bendera merah-putih berbagai ukuran yang diperjual-belikan di pinggiran jalan, tangis Rah pun cukup menyayat. Rah, ketika itu, digebuk bapaknya lantaran memaksa minta dibelikan bendera baru. “Rah memang nakal kok, Dik. Bapaknya sudah membeli bendera kok masih minta dibelikan bendera lagi,” begitu tutur ibunya pada saya. “Maunya sih ingin punya bendera sendiri, yang lebih kecil, yang bisa dibawa untuk karnaval di sekolah. Tapi, untuk karnaval itu kan bisa dengan bendera kertas. Bapaknya pun telah berjanji mau membuatkannya. Tapi, Rah nggak mau. Rah minta dibelikan bendera sungguhan. Bendera kain. Lha, itu kan namanya pemborosan,” jelasnya.
Di lain waktu, Rah menangis digebuk bapaknya, justru karena ia menolak makan daging. “Rah itu memang nakal kok, Dik. Maunya sih main anak-anakan melulu. Sampai-sampai ia lupa makan,” kata ibunya.
Rah nakal. Vonis itulah yang sering saya dengar. Dan, justru ibunya sendiri yang mengatakannya. Ya, Rah nakal. Tepatnya: dianggap nakal. Karena itulah ia kena gebuk. Karena itulah ia sering menangis.
Dan, pagi tadi, ketika saya baru saja membuka jendela, Rah kena gebuk lagi. Rah menangis lagi. Di antara suara tangisnya, saya pun mendengar suara Rah terbata-bata melafalkan teks pancasila.
Pagi tadi, ya pagi tadi peristiwa itu terjadi. Saya baru saja selesai mandi ketika Ning Tin, ibu Rah datang ke rumah saya. “Dik Ri punya obat merah?” selidiknya penuh harap. Dan, saya pun mengangguk mengiyakannya.
Ning Tin butuh obat merah. Dari sini akhirnya saya tahu bahwa Rah kali ini terluka. Benar-benar terluka, setelah tubuhnya diseret-seret dan dihajar oleh bapaknya sendiri. “Kang Pri memang keterlaluan kok, Dik. Wataknya kaku. Apa maunya harus dituruti. Dik Ri tahu sendiri aten-atennya. Kangmu Pri itu moh dibantah. Sementara, Rah sendiri ya ndablek. Seringkali nggak ngreken omongan bapaknya,” kata Ning Tin.
Kang Pri –begitu Ning Tin biasa memanggil suaminya—wataknya memang kasar. Juga tergolong pemberang. Tukang jagal sapi satu-satunya yang ada di kampung saya itu sering marah-marah. Dan, kalau sudah marah, orang-orang di dekatnya nyaris tak ada yang berani membuka mulut. Istrinya, kemenakannya, anak-anaknya, juga semua pembantu kerja pejagalannya, terpaksa diam. Tak ada yang berani memotong kalimat omelannya. Jika ada yang berani menyela kata, bisa dipastikan semua barang di dekatnya hancur berantakan.
Menurut Ning Tin, Kang Pri itu punya penyakit dog- nyeng. Sebentar marah, sebentar pula ia merasa kegetunen. Jelasnya, marah Kang Pri tak pernah berlarut-larut. Setelah memuntahkan amarahnya, seringkali Kang Pri merasa menyesali diri. Bahkan, seringkali pula, hal-hal yang menyulut kemarahannya, justru dijadikan bahan kelakar setelah ia tak marah lagi.
Pernah, dalam sebuah kesempatan ngobrol, Kang Pri bercerita pada saya sembari tertawa-tawa. Saat itu ia menyinggung soal Rah yang menolak diciumnya. Alasan Rah, karena mulut Kang Pri bau. Dan, karena Rah tidak mau dicium, Kang Pri marah-marah. Rah pun digebukinya. “Setelah saya pikir-pikir, ternyata Rah benar. Mulut saya memang baunya amit-amit. Saya sendiri juga jijik. Tapi, istri saya kok betah ya?” katanya penuh canda.
Persoalan yang menyulut amarah Kang Pri, kadang memang terlalu sepele. Tadi pagi, misalnya, ia marah-marah karena Rah bermain anak-anakan sembari bernyanyi-nyanyi di dekatnya. Saat itu Kang Pri sedang sibuk menguliti sapi yang baru saja disembelihnya. Rah dianggap mengganggu kerja. Karena Rah tak mengindahkan perintah, agar sedikit menjauh, Kang Pri mendadak marah. Boneka yang tengah dipeluk Rah segera direbut dan dibuangnya. Setidaknya, begitulah penjelasan Ning Tin pada saya saat mengembalikan sebotol obat merah yang dipinjamnya.
Dan, yang pasti, saya baru saja membuka jendela ketika peristiwa itu terjadi. Saya melihat ada sebuah boneka plastik berlumur darah sapi tergeletak di pelataran rumah. Saat itulah, dengan langkah tertatih, Rah datang mendekat dan menangisinya.
Sebelum Rah diseret-seret oleh bapaknya sendiri, saya melihat ia sempat menggores-gores tanah dengan sebilah tatal kayu di sekitar tubuh boneka. Siswi kelas tiga esde itu seakan membuat tengara kesedihan bergaris-garis tanpa aturan di tengah pijakan, untuk mengenang boneka yang dianggapnya telah mati terbunuh. Dan, saat itu juga, secara kebetulan, saya pun mendengar irama tembang langgam Jawa yang tersuarakan lewat tape recorder: “…golekan, kae golekane sapa. Yen sira tansah dadi golek-golekan, ingsun mengko entek mimis pira”.
Beberapa saat setelah mendengar suara Rah yang terbata-bata melafalkan teks pancasila sambil menangis, saya pun melihat seorang bocah perempuan berpakaian seragam esde itu melangkah tertatih mendekati boneka yang masih tergeletak di pelataran rumah. Kemudian tahulah saya, Bahwa Rah ternyata sangat menyayangi boneka mainannya. Boneka yang berlumur darah sapi itu pun kembali diemban-ayunkannya. Rah seakan tak peduli jemarinya belepotan amis darah. Juga tak peduli baju seragamnya penuh bercak warna merah. Dan, kalau melihat sorot matanya, tampaknya Rah menaruh dendam dan rasa benci pada bapaknya sendiri. Entah kekuatan apa yang merasuki Rah. Yang jelas, sebelum melangkah meninggalkan pelataran rumah, Rah meraup segenggam batu kerikil yang banyak berserak di tanah pijaknya. Lalu, dengan sekuat tenaga, batu-batu kerikil itu dilemparkannya, mengarah ke punggung bapaknya sendiri yang ketika itu sedang sibuk menguliti sapi hasil jagalannya.[]
[Karya Darma, 13 Maret 1997]